Oleh Ketua PMII Komisariat IAIT M. SABIQ A
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam sejarahnya bukan sekadar organisasi kader. Tetapi episentrum reproduksi intelektual Islam progresif yang berakar pada tradisi Ahlussunnah wal Jama’ah dan wawasan kebangsaan yang transformatif. Namun, belakangan ini PMII menghadapi krisis paradigmatik yang serius. Disorientasi arah gerak, disintegrasi ideologis, hingga kooptasi struktural oleh kekuatan politik praktis dan oligarki kekuasaan.
Jika dahulu PMII menjadi arena kaderisasi ideologis dan ruang artikulasi wacana kritis terhadap ketimpangan sosial, hari ini yang terlihat justru cenderung kepada formalisasi gerakan: seremonialisme, loyalitas patron-klien, dan politik akses. PMII nyaris tak lagi bicara soal gagasan, tapi lebih sibuk soal posisi, akomodasi struktural, dan upaya eksistensi simbolik.
Gerakan mahasiswa, menurut teori new social movement seperti yang dikemukakan Alain Touraine dan Jürgen Habermas. Seharusnya menjadi antitesis terhadap hegemoni kekuasaan dan kapital. PMII sebagai bagian dari gerakan mahasiswa seharusnya mengartikulasikan kritik struktural, memproduksi diskursus alternatif, dan membangun kontrak sosial baru bagi umat dan bangsa.
Namun kini, realitas gerakan PMII justru menunjukan paradoks. Apa yang terjadi di lapangan lebih mencerminkan pola gerakan pragmatis, di mana struktur organisasi digunakan sebagai alat negosiasi politik, bukan sebagai medium penyadaran. Alih-alih menjadi agen perubahan (agent of change), PMII terjebak menjadi agen legitimasi kebijakan status quo, lebih banyak menjadi aktor audiensi daripada motor perubahan.
Krisis lain yang tidak kalah serius adalah transformasi Ikatan Alumni (IKA PMII) dari jembatan ideologis antar-generasi menjadi arena pertarungan politis antar-kelompok elit. Patronase alumni menyebabkan kaderisasi di tingkat bawah mengalami distorsi: arah ideologis ditentukan bukan oleh konteks sosial-kultural kader, tapi oleh afiliasi senior ke partai, lembaga, atau proyek tertentu.
Dalam banyak kasus, loyalty-based recruitment telah menggantikan merit-based cadre development. Kader tidak lagi diuji berdasarkan kapabilitas intelektual dan militansi sosialnya, tetapi seberapa kuat loyalitasnya terhadap salah satu kubu alumni. Situasi ini menciptakan politik faksionalisme yang menggerogoti integritas dan independensi kaderisasi.
Bahkan lebih parah, banyak kader muda kini diarahkan untuk menjadi “pengikut” bukan “pemikir”. Ideological autonomy yang seharusnya dimiliki oleh setiap kader tercerabut oleh kepentingan senior yang mengakar dalam kekuasaan. Maka jangan heran jika yang tumbuh bukan pejuang, tapi oportunis berbalut jaket biru.
PMII seolah berjalan dalam mode otomatis. Tidak ada haluan ideologis yang tegas dan jernih. Dalam pidato resmi, PMII mengklaim diri sebagai organisasi kader berbasis nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Tapi dalam praktik, nilai itu kerap dikalahkan oleh realitas struktural: relasi kuasa, kompetisi jabatan, dan kepentingan anggaran.
Banyak cabang dan komisariat berjalan tanpa arah. Kegiatan hanya berbasis event-based approach bukan issue-based movement. Pendidikan formal digantikan oleh pelatihan proyek. Pengkaderan menjadi ritual tanpa ruh, dan ideologi menjadi jargon tanpa pembacaan kontekstual. Padahal, seperti ditegaskan oleh Paulo Freire, pendidikan kader seharusnya merupakan praksis kesadaran kritis yang membebaskan, bukan mendisiplinkan dalam logika kekuasaan.
Dalam situasi seperti ini, kader PMII tidak boleh diam. Kita harus menyadari bahwa krisis ini bukan hanya tanggung jawab struktur pusat, tapi juga refleksi dari pasifnya kader di tingkat bawah yang terlalu lama terdiam atau ikut arus. Kita harus berani membangun kesadaran baru, memperkuat collective critical consciousness, dan menegaskan kembali posisi PMII sebagai gerakan kader berbasis ilmu, nilai, dan keberpihakan terhadap kaum mustadh’afin.
Gerakan PMII ke depan harus kembali menjadi “mesin gagasan” yang memproduksi wacana tanding terhadap narasi arus utama kekuasaan. Kita tidak bisa hanya menjadi “gerbong yang ikut ditarik”, tapi harus menjadi “rel alternatif” bagi arah transformasi sosial. Menjadi kader bukan tentang siapa yang kamu ikuti, tapi apa yang kamu perjuangkan.
PMII tidak akan punah oleh represi eksternal, tapi bisa runtuh oleh pembusukan internal. Jika kita terus membiarkan organisasi ini dikendalikan oleh nalar pragmatis dan faksionalisme alumni, maka bukan tidak mungkin PMII hanya akan menjadi artefak sejarah — dikenang, tapi tidak lagi relevan.
Saya, sebagai kader dan Ketua Komisariat PMII IAIT, mengajak semua kader di manapun berada: berhenti jadi penonton, jadilah pelopor. Refleksi kritis ini bukan bentuk pembangkangan, tapi cinta yang paling jujur: karena kita ingin PMII bukan hanya bertahan tapi juga bermakna.














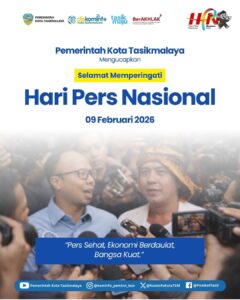
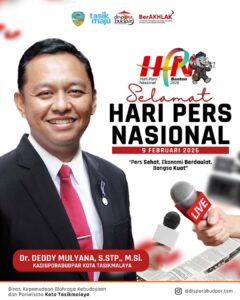
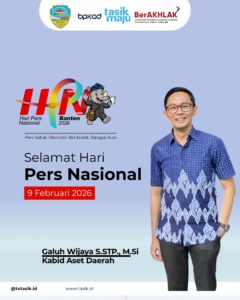







Comment